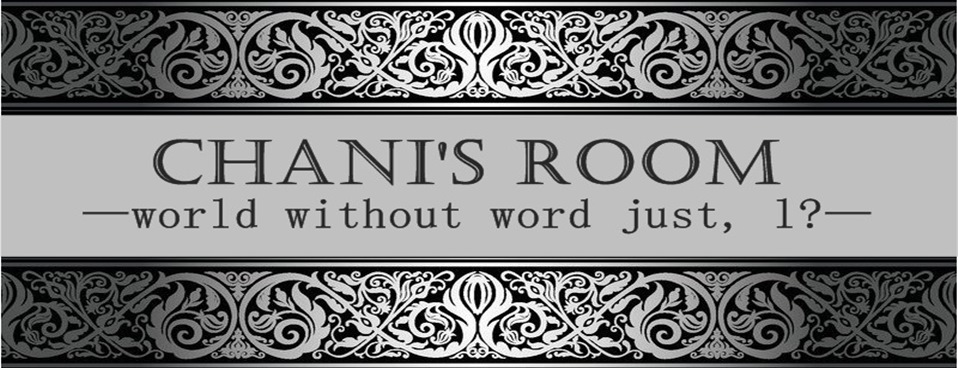Dewi Chani presents
An Alternate Universe request fiction
“FOUR SEASONS—Summer: My Sun”
Length: 1 of 4 season
Summary: Cinta yang benar dalam keadaan yang salah. Lelaki berjambul dengan senyum hangat dan gadis bernama Lily Aron bersama es krim vanillanya. Tahukah mereka bahwa Tuhan sedang menuliskan akhir kisah mereka?
Happy reading!
Mentari itu masih terlukis rapih di kanvas langit.
Terik tajamnya menembus celah-celah awan.
Angin terbang bersama harum khas musim panas.
Dan sebuah es krim vanilla mulai mencair.
Pemiliknya tak menyadari itu.
“Ly, es krimmu!” Lelaki berjambul berteriak pada gadis disebelahnya.
Gadis itu baru tersadar dari melamun dan membulatkan kedua matanya sempurna melihat es krim vanillanya yang mencair lalu mulai menetes ke tangan. Dia berdecak sebal dan jelas itu mengundang tawa renyah lelaki berjambul tadi. “Siapa yang menyuruhmu melamun, Ly?”
Gadis itu mendelik, “Siapa yang ingin makan es krim di tempat panas seperti ini, Jein?”
“Well, jadi kau menyalahkan mataharinya, Ly?”
“Well, apa menurutmu aku bisa menyalahkan benda mati, Jein?”
“Baiklah-baiklah. Bersihkan tanganmu dulu, dasar anak kecil,” Jein –lelaki berjambul itu— menyodorkan sebuah sapu tangan putih polos pada gadis itu.
Lily sibuk membersihkan tangannya sampai ia melihat rajutan huruf L dan A warna merah di sisi kanan bawah sapu tangan itu. “Ini sapu tanganku yang kau pinjam bertahun-tahun itu, kan?”
Jein tersenyum semanis mungkin dengan matanya yang disipitkan, “Aku hanya belum sempat mengembalikkannya, Ly. Kau tahu kan, aku sangat sibuk?”
Lily memutar bola matanya tak perduli, lalu melemparkan sapu tangan putih itu pada Jein. “Cuci dulu, baru kembalikkan padaku.”
“Siapa juga yang membuatnya kotor,” desis Jein setelah menerimanya.
“Apa?”
“Ah? Tidak apa-apa. Aku hanya melihat ada kucing yang menjulurkan lidahnya padaku.”
“Lucu sekali,” sinis Lily.
“Terimakasih.”
***
Jein merendahkan tubuhnya, “Baiklah tuan putri, sudah sampai di istana.”
“Baiklah prajurit, terimakasih tumpangan punggungnya.”
“Tapi lain kali mungkin kau bisa diet dulu.”
“Jein! Aku tidak seberat itu!”
“Aku yang menggedongmu, jadi aku yang tahu seberapa berat tubuhmu.”
“Tapi, aku rasa—“
“Sudah kubilang kan, jangan menggunakkan perasaan. Tapi lihat saja faktanya, nona.”
“Itu bukan fakta. Tapi hanya opinimu, tuan.”
“Dan aku ini orangnya objektif. Jadi menyatakkan opini berdasarkan fakta.”
“Oke, aku akan diet. Puas?”
“Aku hanya bercanda, Lily Aron…”
***
Zayn Malik, atau Jein –begitu caranya memanggil lelaki itu— adalah sahabat baik Lily. Lelaki dengan rambut berjambul, mata hazel, dan jangan lupakan senyuman sihirnya itu. Senyuman sihir? Benar. Senyuman lembut yang selalu berhasil menghipnotis Lily.
Tubuhnya mendadak lemas setiap senyuman sihir itu memasuki saluran penglihatannya.
Seperti matahari yang melelehkan es krim vanilla-nya.
Jein memang benar-benar seperti matahari, bagi Lily Aron. Menghangatkan dan selalu memancarkan sinar.
***
“Jein?”
“Hm?”
“Kau tahu?”
“Tidak.”
“Aku serius.”
“Baiklah, katakan.”
“Kau terlihat seperti matahari bagiku.”
“Benarkah?”
“Dan reaksimu cuma seperti ini?”
“Memangnya aku harus menjawab seperti apa?”
“Jein, aku baru saja mengakui sesuatu yang…. bodoh. Lupakan saja.”
“Gaya bicaramu seperti gadis yang sedang menyatakkan perasaanya kepada senior yang di sukai, Ly.”
“Lalu?”
“Kita sahabat, bodoh.”
“Kau benar.”
***
Lily tidak bisa tidur semalam karena memikirkan untuk mengatakkannya atau tidak.
Lily berbicara sendiri di depan cermin seperti orang gila hanya untuk merangkai kata-kata yang tepat.
Bahkan Lily membuat dialog buatan –antara dia dan Jein— dengan berbagai hal yang paling berkemungkinan besar akan dibicarakan.
Lalu ketika Lily mengatakkan apa arti lelaki itu baginya, yang ia dapatkan hanya sebuah ‘benarkah?’.
Ya, benar. Ini memang benar-benar bodoh.
Dan apa yang lelaki itu bilang? Gaya bicaranya seperti gadis yang sedang menyatakkan perasaanya kepada senior yang di sukai? Oh Tuhan, yang benar saja? Jelas-jelas mereka sahabat.
Ya, sahabat.
Lalu setiap mendengar itu…
Kenapa jatungnya mencelos?
Kenapa nafasnya tercekat?
Kenapa seperti ada lubang menganga di hatinya?
Kenapa air mata mendesak keluar dari matanya?
Lily tidak bisa menyangkal lagi kepada hatinya sendiri kalau dia mulai berharap semuanya lebih dari sekedar sahabat. Tapi dia tidak akan mengakui itu kepada siapapun, karena jika diakui, dia tahu ini akan semakin terasa nyata.
***
Zayn menempelkan ponsel ditelinganya. Lalu tersenyum mendengar suara dari sebrang sana.
“Hallo,”
“Ly?”
“Jein?”
“Apa aku mengganggumu?”
“Tidak. Ada apa?”
“Besok aku tidak bisa berangkat ke sekolah bersamamu.”
“Kenapa?”
“Aku tidak masuk.”
“Kau sakit? Berikan surat doktermu padaku biar—“
Jein memotong ucapan Lily yang tidak memberikkannya kesempatan untuk menjawab, “Aku tidak sakit.”
“Lalu?”
“Pergi.”
“Kemana?”
‘Oh Tuhan, kenapa gadis ini seperti wartawan?’ Jein menggurutu dalam hati.
“Ada urusan keluarga.”
“Oh baiklah, aku akan menyampaikannya pada Mrs. Lauren.”
“Jangan—”
“Ha?”
“Maksudku, tidak perlu. Orang tuaku sudah menghubunginya.”
“Oke. Kapan kau kembali?”
“Aku tidak tahu,”
‘Atau mungkin tidak akan kembali lagi.’ Desisnya lagi dalam hati.
“Kenapa begitu?”
“Tapi mungkin aku akan pergi untuk waktu yang cukup lama.”
“Menyebalkan sekali.”
“Mungkin kau harus membiasakan diri untuk jalan sendiri ke halte bus mulai sekarang.”
“Jein,”
“Ya?”
Dan gadis itu tidak menjawab apapun.
“Hei, kau masih disana?”
“Eh? Ah maaf, aku melamun.”
“Apa yang kau pikirkan, Ly?”
“Apa kau baik-baik saja?”
“Apa? Aku? Ten—tu saja. Kenapa?”
“Tidak, hanya memastikan.”
“Kurasa kau mulai mengantuk. Aku akan menutup teleponnya.”
“Tunggu. Jangan ditutup dulu.”
“Apa lagi—“
“Aku mencintaimu.”
Zayn tidak bisa bernafas dengan baik. Dia benar-benar butuh oksigen lebih banyak di sekitarnya. Mata hazelnya ditutup. Kalimat yang sangat tidak ingin di dengar telinganya, akhirnya terucap.
Ya, tidak ingin di dengar. Bodoh sekali.
Seekor semut di lantai dekat kakinya pun tahu Zayn Malik tidak bisa untuk tidak berharap tentang perasaan Lily Aron padanya, walaupun harapan itu sangat kecil— tapi setidaknya ia masih punya harapan.
“Tidurlah.”
“Aku mencintaimu, Jein.”
‘Aku juga, Ly. Aku juga.’
Tapi tenggorokkannya tertahan, logikanya mencoba mengalahkan perasaan menggebu –gebu itu dihatinya. Tidak. Tidak bisa. Semua bagian tubuhnya pun tahu bahwa dia tidak bisa memiliki perasaan ini. Cukup di dalam hati, jangan sampai terucap.
“Selamat malam. Aku tutup teleponnya.”
***
Lily sadar kalau Jein beberapa waktu belakangan ini berubah semenjak dia mengatakkan kalau lelaki itu seperti matahari. Pasti dia sudah merasakan perasaan Lily padanya lalu merasa tidak nyaman. Mungkin karena Jein tidak memliki perasaan yang sama padanya? Ah benar, lelaki itu sering bilang kalu mereka sahabat. Bodoh.
Lily tahu kalau dia –sangat— gegabah sampai mengatakkan kalimat bedebah itu. Lily Aron telah mengatakkan kalau gadis itu mencintai Zayn Malik yang notabene adalah sahabatnya sendiri.
Tapi dia tidak bisa menahan perasaan lega yang membuncah ini. Rasanya seperti membunuh nyamuk yang sedari tadi mengigiti kulitnya. Baiklah, setidaknya biarkan beban di hati dan pikirannya terasa lebih ringan sekarang.
Jadi mencintai Jein adalah beban?
Sama sekali tidak. Tapi posisinya yang membuatnya merasa terbebani.
Kenapa cinta itu hadir diantara persahabatannya?
Atau malah, kenapa persahabatan itu merusak cintanya?
Lily tidak tahu mana pertanyaan yang tepat.
***
Alat optik itu terbuka dan memperlihatkan kornea hazel yang sontak menyipit karena belum siap menerima bias cahaya mentari. Empunya mengerang menerima sakit di kepalanya. Dia baru akan berpikir tentang ruangan asing ini ketika indra penciumannya mendeteksi bau obat.
Tempat ini lagi.
Sampai kapan dia harus terjaga dari tidur dan mendapati tubuhnya terbaring di ruangan yang selalu tampak asing dengan cat putih di seluruh penjurunya?
Jein baru akan memejamkan matanya lagi ketika ada suara kusen berdecit lalu wanita separuh baya muncul dari balik pintu itu.
“Selamat pagi.”
Wanita dengan wajah khas negara barat yang tetap terlihat cantik walaupun memiliki semburat keriput tipis itu terus menampilkan senyum lembutnya.
“Mau makan bubur?” katanya sambil menaruh plastik bawaannya di atas meja.
“Apa aku pingsan lagi, Bu?”
Jein memang selalu menjawab pertanyaan orang dengan pertanyaan lainnya. Kebiasaan buruk.
Wanita yang di panggil ‘ibu’ itu menghampiri ranjang anaknya lalu duduk di tepi kasur yang kosong, “Ayah menemukkanmu jatuh sambil menggengam ponsel.”
Menggengam ponsel? Apa dia menghubungi seseorang semalam? Oh benar, bahkan teman bicaranya itu menyatakkan cinta.
Zayn menghela nafas berat mengingat suara gadis itu, bahkan setiap katanya.
“Apa dia sudah tahu—“
“Kita sudah pernah membahas itu sebelumnya, Bu.”
“Apa alasannya? Karena ini bukan waktu yang tepat?” Zayn tidak begerming sedikit pun, “Waktu tidak pernah tepat, kalau manusia selalu saja belum siap.”
“Aku memang benar-benar belum siap, Bu.”
“Kurasa kau bisa membedakan antara belum dan tidak. Belum itu berarti akan, kan?”
“Tentu saja, nanti.”
“Sebenarnya aku benar-benar tidak ingin mengatakkan ini –apalagi pada anakku sendiri. Tapi kenapa kau seenaknya selalu mengatakkan ‘nanti’? Kau merasa dirimu dalam keadaan baik-baik saja dan punya banyak waktu, Zayn?”
Kulitnya seperti tertancap runcing kayu lalu mengeluarkan darah. Ibunya baru saja menamparnya kembali pada kenyataan.
“Ibu tahu ini bukan urusan ibu. Tapi setidaknya jangan membuat dirimu lebih menderita dari sebelumnya. Lagipula, kurasa dia juga punya hak untuk tahu.”
***
Lily Aron menatap pintu yang bertuliskan “teachers room”dihadapannya. Lalu gadis berambut hitam itu mendorong pintunya pelan, dan mendongakkan sedikit kepalanya kedalam ruangan. Dia tersenyum saat mendapati sesosok wanita separuh baya melambaikan tangan padanya disana. Ia mendorong pintunya sedikit lagi agar cukup untuknya masuk, lalu berjalan mengahampiri wanita itu.
“Ini tugasku, Mrs.”
Wanita dengan lipstick merah darah itu tersenyum simpul, “Untuk pertama kali, murid yang paling teladan dikelasku telat mengumpulkan tugasnya.”
Lily menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil tersenyum kikuk. “Ah ya, maaf kan aku, Mrs. Banyak hal yang harus kulakukan minggu ini.”
“Hal seperti merindukkan Zayn Malik?”
“Mrs. Lauren—“
Wali kelasnya itu –Mrs. Lauren— mengadah-ngadahkan telapak tangannya sambil tertawa kecil. “Tidak-tidak, kau tidak perlu menjawabnya. Kau tahu kan, aku hanya suka menggodamu.”
“Em,“ Lily memiringkan kepalanya seperti menimbang-nimbang, “Tapi kau benar.”
“Ah baiklah Ly, aku tahu itu sangat menyiksa saat kau merindukkan seseorang,” Mrs. Laurent memegang pundak Lily dengan mimik prihatinnya. “Kuharap dia cepat sembuh.”
Gadis bermarga Aron itu menyernyitkan dahinya bingung.”Sembuh?”
“Kau tidak tahu?”
“Jadi ada sesuatu yang tidak kuketahui, Mrs?”
“Ly…” Mrs. Laurent melepaskan tangannya dari pundak Lily, “Aku tidak bermaksud untuk menyembunyikan ini, tapi mungkin ini bukan kapasitasku untuk bicara.”
“Katakan padaku, Mrs, kumohon. Aku mencintainya.” Entah apa yang gadis itu pikirkan, tapi semua kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Tidak peduli lagi dengan; bodoh-harga diri-sahabat.
Mrs. Laurent menghela nafas panjang seperti meyakinkan dirinya untuk berbicara. “Zayn Malik menderita penyakit hepatitis. Sekarang dia sedang menjalani perawatan intensif.”
Bagi Lily Aron Bumi seperti berhenti berputar.
***
Lily Aron turun dari taksi dengan terburu-buru. Dia berlari ke arah sebuah gedung di sebrang jalan. Hatinya berkecamuk, pikirannya tak bisa fokus sama sekali, satu-satunya hal yang dia ingat adalah Zayn Malik.
Dia menemukannya. Sebuah kamar dengan wanita paruh baya yang sangat tidak asing sedang duduk didepannya, Ibu Jein. Gadis itu benar-benar takut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak bisa untuk menerima kenyataan apapun. Mungkin dia tidak bisa, tapi dia tahu kalau dia harus. Dengan sisa rasa berani yang masih ada dalam dirinya, kaki lemas itu mulai melangkah.
“Mrs. Malik?”
Wanita berambut pendek itu mengangkat kepalanya yang sedari tadi menunduk, menampilkan wajahnya yang penuh air mata. Ibu Jein menangis.
Lily Aron tahu dia semakin dekat dengan kenyataan itu.
Ibu Jein menatapnya dengan pandangan tak percaya. “Ly?”
“Mrs. Lauren mengatakkannya padaku.”
“Aku benar-benar minta maaf…”
“Aku mengerti, Mrs.”
Wanita yang menyandang status sebagai ibu Zayn Malik itu memeluk Lily, menangis di pundak gadis itu. Seperti mencurahkan semuanya hal yang telah terjadi, menceritakkan semua kesedihan yang selama ini ia rasakan.
Ibu Jein melepaskan pelukannya, “Anak nakal itu selalu memarahiku kalau tahu aku menangisinya.”
Lily baru ingin menanggapi kalimat Ibu Jein ketika pria berjas putih keluar dari ruangan –yang Lily tahu ada Jein di dalamnya.
“Daniel?” Ibu Jein menghapus air matanya lalu menghampiri dokter —yang dipanggilnya Daniel itu— dengan tersenyum penuh harap.
“Maafkan aku, Mrs.” Daniel menundukkan kepalanya seperti menyesal.
Lily tahu kali ini ia sudah sangat dekat dengan kenyataan itu.
Senyum penuh harap milik Ibu Jein seketika luntur begitu saja, wanita itu sontak berlari memasuki ruangan di balik tubuh Daniel. Sedetik kemudian Lily bisa mendengar jeritan tangis Mrs. Malik dari luar.
Kali ini kenyataan itu memang sudah ada dihadapannya.
Tangan bergetar gadis itu memutar gagang pintu besi yang kali ini terasa seribu kali lebih dingin dari biasanya. Suara decitan kusen, menandakan pintu itu terbuka. Menampilkan jelas isi ruangan itu.
Tak pernah terbayangkan sebelumnya, melihat lelaki itu tergeletak lemas tak berdaya. Ia bisa melihat jelas wajah pucat yang kini semakin tirus, kornea hazel indah dibalik kelopak mata yang menutup, dada dan perut yang tenang karena empunya sudah tidak bernapas.
Lily tidak percaya pada matanya yang terasa panas, pada tubuhnya yang gemetar hebat, pada pandangannya yang mulai buram, pada rahangnya yang merapat, dan bahkan pada cairan tak berwarna yang lolos dari pelupuk matanya.
Dia tidak seharusnya menangis, tak ada perlu di tangisi, Zayn Malik baik-baik saja. Lelaki menyebalkan itu tak akan pernah meninggalkan nya sendiri begitu saja. Lelaki itu pasti akan menghapus air matanya dan memeluknya.
Tapi kenapa dia tidak bisa berhenti menangis…
Kenapa lelaki itu tidak memeluknya..
***
Hal yang paling buruk dari di tinggalkan adalah merasa kehilangan. Tahap dimana harus menerima kenyataan bahwa sosok itu sudah tidak ada lagi.
Bahkan Lily berharap, kalau lebih baik Zayn Malik sengaja menjauh karena mengetahui perasaan gadis itu padanya. Karena dengan begitu, setidaknya… Ia masih bisa melihatnya, mendengarnya, merasakan kehadirannya di sekelilingnya. Memastikan apa lelaki itu dalam keadaan baik-baik saja. Daripada ia tidak dapat melihatnya lagi, walau hanya bayangannya. Tidak dapat mendengarnya, walau hanya suara langkah kakinya. Tidak dapat merasakan kehadirannya, walau hanya harum parfumnya.
Karena lelaki itu memang tidak akan kembali lagi. Walau hanya untuk sekedar mengucapkan selamat tinggal.
“Ly…”
“Berhentilah menyiksa dirimu sendiri, aku yakin Jein akan marah jika melihatmu seperti ini.”
“Bacalah. Jein menulisnya sebelum pergi.”
***
Dear Lily, bunga musim panasku…
Aku tak tahu apa tujuanku menulis ini. Mungkin ini terlihat seperti drama-drama, tapi— mungkin aku tidak bisa mengungkapkan kalimat-kalimat sepuitis ini secara langsung padamu. Bukan tidak mau Ly, aku tidak bisa. Kau tahu, bukan sekarang? Penyakit hepatitis ini membuatku terlihat sangat lemah. Bodoh. Pengecut. Bahkan untuk sekedar mengungkapkan perasaanku pada gadis yang kusukai saja tidak bisa.
Ly, aku sakit. Disini, di dadaku rasanya sakit sekali. Aku lelah seperti ini. Tapi aku menahannya. Karena aku punya hal yang dapat membuatku bertahan. Bukan obat-obatan, tapi kau.
Aku sangat merasa tidak adil saat aku hidup ditemani penyakit yang menggerogoti tubuhku. Tapi aku sangat berterimakasih pada Tuhan karena mempertemukan kita.
Aku menyayangimu, Ly. Aku mencintaimu, Lily Aron.
Aku suka ketika kita bertukar pikiran, mengomentari berita-berita televisi, atau bercerita sedikit tentang masa kecil masing-masing, dan sekedar mengisi memoriku yang hampa. Terimakasih, terimakasih. Karena telah memberikkan secuil kenangan yang dapat kubanggakan.
Carilah lelaki yang dapat memberikkanmu hal yang lebih baik dari apa yang ku berikkan padamu.
Berbahagialah Ly, demi aku.
Your friend,
Zayn
Setiap kalimat bahkan kosakata itu tak berhentinya di tatap, seakan-akan semua huruf dan spasi itu punya kaki dan akan pergi dari kertasnya. Tapi menurut Lily Aron kalau memang huruf dan spasi itu ingin pergi, silahkan saja, tapi terkecuali satu kalimat itu. Biarkanlah ia tetap disitu.
Aku menyayangimu, Ly. Aku mencintaimu, Lily Aron.
Tidak ada kalimat yang lebih penting dari itu.
Setidaknya masih ada satu alasan untuk dia terus bernapas.
Karena, Zayn Malik mencintainya.
END